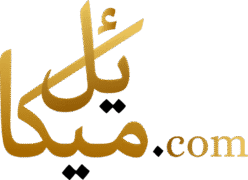Oleh: Abu Fatiah Al-Adnani | Pakar Kajian Akhir Zaman
Bila kita ingin melihat seperti apa praktek ukhuwah imaniyah yang dilakukan di era nubuwah, maka kisah para Sahabat nabi adalah gambaran yang paling ideal . Mereka mampu mewujudkan gambaran mukmin yang satu dengan lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan.
مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi dan menyayangi adalah seperti sebuah tubuh, jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit”. HR. Muslim
Riwayat Al-Baihaqi dalam Asy Syu’ab menyebutkan, salah seorang sahabat Nabi SAW suatu hari diberi hadiah berupa kepala kambing, kemudian ia berkata “Sesungguhnya si fulan dan keluarganya lebih membutuhkan ini daripada kita.” Kemudian ia mengirimkan hadiah tersebut kepada yang lain, dan secara terus-menerus hadiah itu dikirimkan dari satu orang ke orang yang lain sampai akhirnya kembali kepada sahabat yang pertama kali memberikan.
Abdurrahman bin Auf juga mengisahkan bahwa ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan dirinya dengan Sa’ad bin Ar Rabi’. Saat Abdurrahman datang, Sa’ad berkata, “Sesungguhnya aku adalah orang Anshar yang paling kaya. Aku akan bagikan untukmu separuh hartaku, dan silakan kau pilih mana di antara dua istriku yang kau inginkan, maka akan aku lepaskan ia untuk kau nihahi.” Namun Abdurrahman berkata, “Tidak usah, aku tidak membutuhkan yang demikian itu.”
Ada lagi seorang sahabat nabi yang kedatangan tamu, tetapi ia tidak memiliki sesuatu untuk menjamu tamu tersebut. Ia hanya memiliki persediaan makanan untuk anak-anaknya saja, dan itu pun sangat sedikit. Sahabat itu kemudian meminta istrinya untuk mengajak anak-anaknya bermain, dan jika mereka lapar, ia meminta istrinya untuk mengajak mereka tidur. Ketika tamunya masuk ke dalam rumah, sahabat itu lantas memadamkan lampu ruang makannya, dan menunjukkan seolah-olah dirinya sedang makan bersama tamu tersebut. Padahal sebenarnya ia, istri, dan anak-anaknya tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya, pergilah sahabat dan istrinya ke Rasulullah SAW, dan Rasul pun memberitakan pujian Allah SWT terhadap mereka berdua. Rasul berkata, “Sungguh, Allah SWT merasa heran dan kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian, maka Allah menurunkan Ayat 9 surat Al-Hasyr.”
Begitulah praktek ukhuwah di masa generasi terbaik. Sikap amanah, jujur, adil, terpercaya (shidq), itsar (lebih mengutamakan orang lain), adalah paket lengkap keadaan mereka yang menjadikan ukhuwah itu sedemikian indah dirasa. Sebab kehidupan mereka terbebas dari segala bentuk fitnah yang membuat ukhuwah menjadi rusak dan cacat. Lalu bagaimana membangun ukhuwah di zaman fitnah?
Akhir zaman adalah kondisi dimana sifat amanah akan tercabut dari dada manusia
Dari Hudzaifah ra, dia berkata:
Rasulullah saw mengabarkan kepada kami 2 perkara yang salah satunya telah aku buktikan, sedangkan yang satunya lagi masih aku tunggu kejadiannya. Pertama, Rasulullah saw mengabarkan bahwasanya sikap amanah itu terletak di hati manusia yang paling dalam. Kemudian mereka mengetahuinya melalui Al-Qur’an yang selanjutnya mereka juga mengetahuinya dari As-Sunnah. Kedua, Rasulullah saw juga mengabarkan bahwa sikap amanah akan dicabut ketika seseorang sedang tidur.
Maka, pada saat itulah amanah dicabut dari hatinya hingga tinggallah bekasnya itu seperti noda yang berwarna. Kemudian orang tersebut tidur lagi, dan dicabutlah amanah dari dalam hatinya (sehingga bekasnya seperti bekas lecet di tangan yang melepuh karena mengangkat beban terlalu berat) atau seperti bekas bara yang terinjak oleh kakimu sehingga telapak kakimu melepuh sedangkan di dalam luka lepuhan tersebut tidak terdapat apa-apa. Seperti itulah manusia nanti, banyak orang telah membaiatnya namun setelah dia menjadi pemimpin dia tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya itu dengan baik.
Pada masa itu orang-orang menggembar-gemborkan bahwa di Bani Fulan terdapat orang yang dapat dipercaya, “Alangkah cerdiknya dia, alangkah lihainya dia, dan alangkah piawainya dia.” Padahal sedikitpun dalam hati orang yang dielu-elukannya itu tidak terdapat secercah sikap amanah dan keimanan. Sungguh telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak peduli lagi kepada siapa di antara kalian aku akan melakukan transaksi jual-beli. Jika orang yang kuajak transaksi itu adalah seorang muslim maka keislaman akan mencegahnya (dari khianat), dan jika dia adalah orang Nasrani maka pejabat pemerintah mencegahnya (dari khianat). Adapun sekarang ini, aku tidak mau bertransaksi kecuali dengan si fulan dan si fulan.”[1]
Riwayat Huzaifah di atas menggambarkan bahwa gejala berkurangnya sikap amanah ini mulai terjadi pada generasi awal umat Islam sebagaimana yang tersirat dalam redaksi hadits tersebut. Menjelang akhir hayatnya, Hudzaifah ra mulai meragukan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, sampai-sampai dia tidak mau melakukan mubaya‘ah kecuali dengan fulan atau fulan, yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang jumlah sedikit.
Maksud dari mubaya‘ah dalam hadits ini bukanlah bai‘ah (mengangkat) khalifah, tetapi yang dimaksud dengan mubaya‘ah adalah jual-beli. Al-Khathabi berkata, “Sebagian orang ada yang menafsiri hal ini sebagai bai‘ah khilafah, ini sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin mereka bisa menafsirkan dengan seperti itu, padahal redaksinya berbunyi: wa in kâna nashraniyyan raddahu alayya sa’ihi (jika dia orang Nasrani maka pemerintah yang berkuasa akan mencegahnya dari khianat kepadaku). Lantas apakah orang Nasrani bisa dibaiat menjadi khalifah? Yang benar, mubaya’ah (dalam hadits itu) berarti jual-beli.”[2]
Riwayat di atas mengisyaratkan bahwa di zaman tercabutnya amanah, maka seorang mukmin harus berhati hati dalam bermuamalah, terutama saat berurusan dengan masalah uang. Banyak orang yang jujur dalam satu hal, namun ketika berurusan dengan harta, tiba-tiba kejujuran dan amanahnya tergadaikan.
Lantas, bagaimana seorang mukmin tetap bisa menjaga hubungan dengan saudaranya seiman di zaman fitnah yang kejujuran telah menjadi barang yang mahal?
Pada bagian pertama dari tulisan ini sudah disinggung tentang bagaimana keadaan manusia di akhir zaman kelak, dimana Allah akan mencabut sifat amanah dari dada banyak manusia. Berkurangnya amanah yang dirasakan oleh sahabat Hudzaifah ra. ini merupakan pertanda yang selalu berubah dan terjadinya karena akibat dari keadaan masa sebelumnya.
Kandungan hadits tersebut menyatakan bahwa pertanda tercabutnya amanah ini telah begitu kuat di tengah-tengah masyarakat dan hanya beberapa orang saja yang bisa dipercaya. Saking rusaknya sikap amanah, sahabat Huzaifah hanya mau melakukan transaksi jual beli kepada beberapa orang saja.
Bisa dibayangkan, jika Hudzaifah ra saja sudah mulai resah dengan dicabutnya amanah dari hati manusia, padahal mereka itu masih begitu dekat dengan masa Rasulullah saw, lantas bagaimana halnya dengan kondisi kita sekarang ini? Jarak zaman dengan sumber wahyu sudah teramat jauh, hati mereka juga berbeda jauh dengan hati mereka, nilai sudah banyak yang berubah, belum lagi fenomena kemungkaran yang terjadi di mana-mana. Ini semua menunjukkan bahwa di masa sekarang ini, tercabutnya amanah merupakan pertanda hari Kiamat yang benar-benar nyata di hadapan kita.
Bagaimana menjaga ukhuwah di zaman tercabutnya amanah?
Adalah kondisi dilema untuk mewujudkan nilai nilai ukhuwah dalam kehidupan masyarakat muslim yang sifat kejujuran dan amanah sudah meredup bahkan hilang dari kehidupan mereka. Jika dahulu para sahabat justru berlomba memberikan bantuan, penawaran dan hal semisal kepada saudaranya yang membutuhkan, maka hari ini banyak kaum muslimin yang sulit untuk mendapatkan bantuan dari saudaranya tatkala ia benar benar membutuhkan.
Faktornya tentu saja bukan semata karena sifat ‘bakhil’ atau kikirnya mereka yang berharta, namun boleh jadi juga akibat rasa kecewa ketika orang-orang baik itu dikhianati oleh sikap saudaranya yang tidak mampu menjaga amanahnya. Begitu mudahnya mereka menjanjikan kawannya saat meminjam -uang- misalnya. Namun menjelang hari jatuh tempo, seribu satu alasan muncul yang membuatnya tidak bisa menepati janji, dan kejadian itu berulang-ulang.
Atau juga lantaran banyak kasus penipuan yang menggunakan simbol-simbol keshalihan; akhwat berlibab (atau bercadar), ikhwan berjenggot, aktivis masjid, ustadz, atau lainnya. Sehingga orang-orang baik dan jujur itu benar benar kehilangan rasa percaya dengan mereka.
Imam Al-Bukhari membuat satu bab tentang ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ra, dimana Rasulullah saw bersabda:
“Bagaimana jadinya, hai Abdullah bin Amr, jika engkau berada di tengah orang-orang yang rusak akhlaknya. Mereka telah mengumbar janjinya dan mengingkari amanat yang mereka pikul, bahkan mereka berselisih paham dengan orang-orang hingga mereka menjadi seperti ini.” (lalu Rasulullah saw menautkan kedua jari-jari tangannya). Abdullah balik bertanya kepada Rasulullah saw, “Apa yang Anda perintahkan kepadaku (jika saat itu terjadi pada diriku)?” Beliau menjawab, “Hendaklah engkau hanya bergaul dengan orang-orang yang datang dari kalanganmu dan tinggalkan bergaul dengan orang awam.”[3]
Hadits ini mengisyaratkan adanya kontradiksi antara janji yang diberikan dengan sikap amanah yang harus ditunaikan. Kontradiksi ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan ejekan terhadap mereka yang sebenarnya bukanlah orang-orang yang mempunyai sifat amanah, yang dalam hadits sebelumnya diibaratkan dengan dicabutnya sifat amanah.
Di samping itu hadits tersebut juga mempunyai sudut pandang hukum fikih terkait seseorang yang mengalami atau hidup di zaman seperti itu, yaitu hendaknya dia hanya bergaul dengan temannya yang mempunyai sikap amanah jika mampu menemukan kelompok seperti itu. Jadi ini merupakan fikih yang berkaitan dengan sikap yang harus diambil ketika seseorang menemukan kondisi di mana manusia sudah banyak yang rusak.
Maka, di zaman yang manusia sudah rusak janji dan amanahnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang beriman dalam menjaga ukhuwah dan hubungan saudaranya:
- Jika kita berkenalan dengan seorang ikhwah yang diketahui memiliki kecukupan harta misalnya, maka janganlah terburu-buru untuk masuk pada bab ‘meminjam uang’. Kita khawatir ia akan tersiksa dengan perasaannya yang berat untuk menolak menolong kita, namun juga was-was dan khawatir bila kita tidak mampu memenuhi janji.
- Bersikap iffah dan jangan menampakkan diri ‘memelas’ atau butuh belas kasihan, sehingga mereka menjadi tersiksa karena merasa tidak bisa membantu kita.
- Jangan paksa orang lain untuk segera percaya kepada diri kita, sebab mereka memang belum mengenal kita. Namun, paksalah diri kita untuk layak mendapatkan kepercayaan dari mereka. Cara kita memaksa diri kita untuk bisa dipercaya bisa dengan banyak hal. Misalnya saat kita hendak meminjam harta mereka, maka berilah jaminan yang membuat mereka menjadi tentram dan merasa aman. Atau tunjukkan kredibilitas kita, kejujuran dan sikap amanah kita –dalam waktu yang cukup lama – sehingga kita dikenal oleh fulan akan kejujuran dan kredibilitas dalam persoalan harta. Jika sifat itu telah melekat pada diri kita, maka akan banyak orang yang tidak keberatan untuk menolong kita.
- Jika ada orang lain yang hendak meminjam harta kita dalam jumlah yang cukup besar (kalau dibanding dengan kwalitas amanah dan kemampuannya), maka tolaknya permintaannya dengan baik baik. Berikan kepadanya sedekah yang bisa membantu meringankan bebannya. Dengan demikian, kita tetap bisa membantu tanpa harus merasa tersiksa dengan rasa khawatir jika orang itu tidak menepati janjinya.
- Di zaman fitnah yang amanah telah tercabut dari kebanyakan hati manusia, terkadang sumpah dan janji mereka yang menggunakan nama Allah, bahkan hitam di atas putih bermaterai, semua itu tidak memberikan jaminan. Maka, Nabi menyarankan agar kita tidak bermuamalah kecuali dengan orang-orang yang benar kita mengenalnya. Hendaklah engkau hanya bergaul dengan orang-orang yang datang dari kalanganmu dan tinggalkan bergaul dengan orang awam.”[4]
Wallahu a’lam bish shawab
[1] HR. Al-Bukhari, Ar-Riqâq, hadits no. 6497 [Fath Al-Bârî (11/341)].
[2]Fath Al-Bârî, jil.11, hal. 342.
[3] HR. Ath-Thabari dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. [Fath Al-Bârî (13/43)].
[4] HR. Ath-Thabari dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. [Fath Al-Bârî (13/43)].